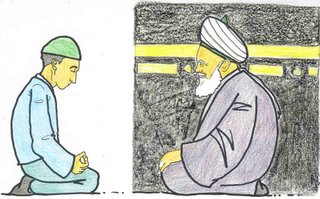 Terjemah Kitāb Fat, al-Mubīn fī Syar, al-Arbaīn :Sebuah Naskah Klasik Sumatera Utara
Terjemah Kitāb Fat, al-Mubīn fī Syar, al-Arbaīn :Sebuah Naskah Klasik Sumatera UtaraPendahuluan Intelektual Muslim masa lampau meninggalkan naskah-naskah dalam jumlah
yang sangat besar. Hasil karya intelektual yang merupakan bagian dari usaha ijtihad dan pengembangan kajian keislaman tersebut tidak akan memiliki makna dan nilai bagi kehidupan masyarakat Muslim kecuali dipelihara, dikaji dan dikembangkan. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan penelitian untuk memahami isi yang dikandungnya dan mengambil intisari yang dapat dikembangkan pada masa kini.
Naskah Terjemah Kitāb Fat? al-Mubīn fī Syar? al-Arbaīn adalah manuskrip yang ditemukan di Desa Mompang Julu, Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Naskah itu disimpan seorang ulama, H.M. Shaleh Nasution. Naskah tersebut berukuran 23,5 x 17 cm, terdiri dari 28 kuras, 12 lembar setiap kuras, dengan jumlah seluruhnya 1340 halaman. Setiap halaman berisi 21 baris berhuruf Jawi (bahasa Melayu berhuruf Arab). Tulisannya bagus dan jelas dengan tinta hitam dan merah. Keadaan naskah sangat baik, tetapi beberapa lembar halaman depan hilang (mungkin terdiri dari dua atau tiga kuras), dan tanpa cap kertas (watermark). Dilihat dari tempat dan masa penulisan naskah (Mekah 1285/ 1868 M) sebagaimana tertulis di kuras ke-25, dipastikan bahwa naskah ini diperoleh ulama Mandailing (kemungkinan Syekh Mustafa) dari penyalin atau penerjemah naskah yaitu Muhammad āli?. Ia seorang ulama dari Patani yang berdiam dan belajar di Mekah, ulama pendiri tarekat Sammāniyyah, yang kemudian oleh Syekh Mustafa naskah tersebut dibawa ke kampung Mandailing. Naskah yang diteliti merupakan naskah terjemahan dari Syar al-Arba`īn. Secara genealogi, Ibn ajar al-aitamī, lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Alī bin ajr Syihāb ad-Dīn Abū al-Abbās al-aitamī (ulama abad ke-16 M) melakukan syarah atas kitab al-Arbaīn adī an-Nawawiyyah fī al-Aādī? a-aīah an-Nabawiyyah karya Imām Muhyi ad-Dīn Yahyā bin Syarf bin Marī an-Nawawī ad-Dimsyiqī (621-676 H/1233-1277 M) yang berisi masalah tauhid dan fiqh. Menurut Muhammad as-Sa`id Farhud, seorang tokoh yang juga melakukan syarah terhadap kitab al-Arba`īn an-Nawawiyyah, terdapat beberapa ulama termasuk Ibn hajar al-haitamī yang telah mensyarah kitab hadis al-Arba`īn an-Nawawī ini. Di antaranya Imām an-Nawawī sendiri, kemudian Syaikh asy-Syabrukhitī, Syaikh as-Sahīmī, asy-Syaikh al-Fusynī, asy-Syabsyīrī, asy-Syarnūbī, an-Nabrāwī, dan al-Jurdīnī. Azra juga mengungkapkan bahwa ulama Melayu yang pernah melakukan syarah atau memberi penjelasan terhadap kitab hadis al-Arba`īn adalah Abd Raūf as-Sinkilī (w. 1105 H/ 1693 M) atas permintaan Sulhānah Zakiyyah ad-Dīn. Lebih lanjut Azra menjelaskan, kitab al-Arba`īn adalah sebuah koleksi kecil hadis-hadis menyangkut kewajiban-kewajiban dasar dan praktis kaum Muslim yang secara jelas ditujukan untuk pembaca umum dan bukan untuk ahli yang mendalami ilmu agama. Hanya saja hingga sekarang, penjelasan as-Sinkilī atas empat puluh hadis tersebut tidak terdapat dalam bentuk cetakan dan belum diketahui keberadaannya.
Dari naskah yang diteliti tidak diketahui dengan jelas buku mana yang digunakan Muhammad āli, sebagai bahan untuk membuat karya terjemahan, karena beberapa bagian depan dari kuras tersebut hilang. Diperkirakan, pada halaman depan belum tentu dicantumkan nama kitab yang ia terjemahkan. Tetapi, melalui sebuah situs internet www.fathani.org yang menerangkan rangkaian manuskrip Melayu karya ulama-ulama Nusantara, diketahui ia menulis kitab Fat? al-Mubīn fī Syar? al-Arba`īn karya Ibn ajar al-?aitamī, sebagaimana tercantum dalam koleksi manuskrip Fatani. Mu?ammad ?āli adalah seorang ulama Melayu yang berasal dari Patani abad ke-18 yang lama bermukim dan belajar di Haramain. Ia adalah salah seorang guru dai Dāwūd bin Abd Allāh bin Idrīs al-Faānī (w. 1265 H/ 1847 M), seorang ulama yang paling terkenal dari wilayah ini. Melalui Muhammad āli, Dāwūd al-Fatānī belajar dan terlibat langsung dengan tarekat Sammāniyyah yang didirikan oleh Muhammad as-Sammānī. Meskipun tergolong lebih tua dari Dāwūd al-Faānī, tetapi Muhammad āli memiliki umur yang lebih panjang daripada muridnya itu, karena setelah kematian Dāwūd al-Faānī-lah, naskah Terjemahan Kitāb Fat al-Mubīn fī Syar al-Arbaīn ditulis Muhammad āli (1285 H / 1868 M). Di dalam kitab ini, Muhammad āli mengaku sebagai murid seorang syaikh tarekat Sammāniyyah, Khalwātiyyah dan Syāiliyyah. Sebenarnya tarekat Sammāniyyah merupakan gabungan berbagai tarekat dengan nama pendirinya, yaitu Muhammad as-Sammānī yang berafiliasi kepada tarekat-tarekat seperti Khalwātiyyah, Qādiriyyah, Naqsyabandiyyah, Adiliyyah, dan Syāiliyyah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana naskah Terjemah Kitab Fat al-Mubīn fī Syar al-Arbaīn sampai ke negeri Mandailing. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa naskah ini dibawa oleh seorang ulama Mandailing, yaitu orang tua dari H.M. Shaleh Nasution (penyimpan naskah), bernama Syekh Musthafa bin Syekh Syahbuddin Nasution dari kota Haramain. Syekh Musthafa yang lahir pada tahun 1892/93 M. adalah seorang ulama Mandailing yang pernah menetap di Mekah dari tahun 1900 sampai 1915. Bersama dengan seorang ulama terkemuka lainnya, Syekh Musthafa Husein pendiri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, ia berangkat ke Mekah untuk belajar melalui Kedah, Malaysia. Mereka termasuk orang-orang Mandailing pertama (akhir abad ke-19 M) yang belajar ke Mekah. Syekh Musthafa bin Syekh Syahbuddin Nasution adalah seorang ulama yang produktif menulis dan menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Karyanya meliputi bidang ilmu fiqh, tasawuf, tauhid, dan qira`ah. Kemungkinan Terjemah Kitab Fat al-Mubīn fī Syar al-Arbaīn merupakan salah satu naskah yang ia peroleh ketika belajar di Mekah dan dijadikan sebagai bahan dalam kegiatan belajar mengajar di masyarakat Mandailing atau institusi pendidikan seperti pesantren Musthafawiyyah Purba Baru. Keingintahuan peneliti menyangkut isi teks dan asal usul naskah, serta kaitan naskah dengan Islam di negeri Mandailing telah mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam naskah ini. Pertimbangannya, yaitu kondisi fisik naskah masih bagus, jelas, dan dapat dibaca serta dipahami; dan topik yang dibahas dalam naskah tersebut agak luas, dimulai dari bidang tauhid hingga masalah hukum makanan. Selain itu, usia naskah juga telah cukup tua. Penulis mencoba menelusuri genealogi serta memahami dan menganalisis isi manuskrip tersebut. Kritik Teks Secara umum, struktur pembahasan dalam naskah ini cukup sistematis dan konsisten. Urutan penyajian didahului dengan menuliskan sebuah hadis, kemudian terjemahan, selanjutnya matan, sanad, dan periwayat hadis. Penulis menjelaskan secara rinci permasalahan-permasalahan yang terkait dengan matan hadis tersebut dalam bahasa Arab (bertinta merah), kemudian diterjemahkan dan dielaborasi secara rinci didukung dengan kutipan pendapat-pendapat para ahli termasuk Imām Nawāwī sebagai penulis Kitāb al-Arbaīn dan Ibn hajar. Ungkapan dan kata atau berkata (dengan tinta merah) disebutkan lebih dahulu baru nama tokoh atau ahli yang dikutip berserta nama kitabnya. Sesuai dengan kompleksitas pembahasan yang disajikan oleh penulis naskah, dapat dikatakan bahwa kitab ini tidak ditujukan kepada pembaca pemula. Isi naskah ini berbeda dari kitab asalnya yaitu Kitāb al-Arbaīn yang dinilai oleh Azra sebagai sebuah koleksi kecil hadis menyangkut kewajiban-kewajiban dasar dan praktis kaum Muslim yang secara jelas ditujukan untuk pembaca umum dan bukan ahli yang mendalami ilmu agama. Kitab Terjemah Fat al-Mubīn fī Syar al-Arbaīn karya Muhammad āli ini layak dikaji oleh tokoh-tokoh atau mereka yang ingin mengetahui lebih dalam makna dan kaitan sebuah hadis dengan hukum-hukum Islam.
Sebuah catatan yang perlu disampaikan pula bahwa Muhammad āli tidak sepenuhnya menjawikan kitab Fat al-Mubīn karya Ibn hajar al-haitamī, seperti yang ia sebut di kuras terakhir. Tetapi pada beberapa bagian, khususnya bagian akhir naskah, ia memasukkan beberapa bahasan dari kitab lain yang tidak disebutkan sumbernya. Pada bagian ini, di beberapa tempat, penulis tidak konsisten dalam cara menuliskan kata-kata tertentu. Misalnya, ia menulis kata buruan, di beberapa tempat menggunakan huruf waw setelah ba, tetapi pada beberapa tempat lain ia tidak menggunakan huruf waw. Kemudian untuk menulis huruf c ia selalu menggunakan huruf jim sehingga menyulitkan pembaca untuk memahaminya.
Gambaran tentang Budaya Saat itu Abad ke-19 merupakan periode sejarah yang cukup penting dalam perjuangan melawan penjajah di Nusantara. Sejak tahun-tahun awal abad ini rakyat di wilayah ini seolah digerakkan untuk secara konfrontatif melawan penjajah Belanda, hampir di seluruh kepulauan dan daerah. Gerakan Imam Bonjol dengan kaum paderinya di Sumatera Barat dan gerakan Diponegoro di Jawa merupakan bentuk perjuangan yang cukup penting, yang ditandai dengan perang terbuka antara rakyat dengan Belanda dan orang-orang pribumi yang pro Belanda. Dari perspektif keagamaan, gerakan-gerakan yang muncul di Nusantara pada abad ke-19 itu tidak dapat dikatakan sebagai perjuangan yang vis a vis antara rakyat dan kaum penjajah, tetapi juga sebagai pertarungan antara kaum agama dengan kaum adat atau kraton. Perang Paderi di Sumatera Barat, misalnya, pada awalnya dimulai dari konfrontasi antara kaum paderi (Muslim) dengan ninik-mamak (kaum adat).
Demikian juga di Jawa, isolasi Diponegoro dari jajaran keraton Yogyakarta (karena tidak dipilih sebagai Sultan) dapat disebut sebagai faktor penting dalam gerakan umat Islam di sana. Dengan demikian, front-front perjuangan di Nusantara sebagian besar dapat dikategorikan sebagai front perjuangan umat Islam, sekaligus dapat juga dipandang sebagai indikasi menguatnya gerakan umat Islam untuk mendapatkan posisi penting dalam percaturan politik dan kekuasaan. Pada sisi lain, gerakan umat Islam Nusantara abad ke-19 meluas ke aspek lain, terutama dalam bidang keilmuan.
Penyebaran para penuntut ilmu dari berbagai kepulauan Nusantara ke berbagai pusat-pusat pengetahuan Islam, seperti Mekah, adalah bukti bahwa semangat untuk maju sudah mulai menguat. Kegiatan ini dinilai sangat penting, tidak saja untuk kepentingan peningkatan wawasan keislaman itu sendiri, melainkan juga untuk perluasan jaringan antardaerah di Nusantara. Pertemuan para santri Nusantara di Haramain tentu semakin memperkokoh hubungan antara satu sama lain, bukan saja antara santri dari wilayah Indonesia melainkan juga meluas ke santri Melayu lainnya dari kepulauan lain, termasuk dari Malaya, Filipina, Thailand, dan sebagainya. Santri-santri inilah yang kemudian kembali ke Indonesia dan menjadi ulama di daerahnya masing-masing. Banyak hal lain yang menarik mengenai percaturan sosial, politik, dan keagamaan pada abad ke-19 di Indonesia. Satu hal penting yang perlu dicatat di sini adalah kebijakan politik kaum penjajah yang menghapuskan sistem kesultanan di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Palembang dan Aceh. Dalam sejarah pengembangan intelektualitas dan penyebaran Islam di Nusantara, kesultanan ini memainkan peranan yang cukup strategis, sebagai pusat penyebaran Islam dan pusat pengembangan wawasan keilmuan.
Pada masa sebelum kesultanan dihapus oleh Belanda, Kesultanan Palembang dan Aceh merupakan tempat yang nyaman bagi ulama untuk menulis kitab, dan ini menjadi terhambat karena kesultanan sudah dihapus. Dari sudut faham keagamaan, umat Islam Nusantara sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran sufistik, khususnya tasawuf falsafi dan tarekat Syattariyah. Tasawuf falsafi berkembang di bagian utara Sumatera, yang disponsori oleh ?Abd ar-Ra?ūf Singkel, ?amzah Fan?ūrī, dan ar-Rānirī. Pemikiran-pemikiran mereka cukup cemerlang dan mencerahkan, tapi sayang tidak dapat dicerna oleh masyarakat awam. Sedangkan tarekat Syattariyyah berkembang di Sumatera bagian selatan dan Pulau Jawa. Corak keagamaan tarekat ini dipandang kurang mendorong kemajuan. Di Jawa dan juga daerah-daerah lain di Nusantara sering terjadi paduan antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga tidak jarang dikategorikan orang sebagai sinkretisme agama-budaya. Saling melengkapi antara faham sufistik (tarekat Syattariyah) seperti yang dipahami oleh penganutnya dan faham sinkretis serupa tidak menguntungkan, sebab dapat memperkokoh keterbelakangan umat Islam. Faktor inilah kemudian yang mendorong timbulnya pertarungan antara kaum pembaharu dengan penganut faham tradisional. Penelusuran sejarah masa lalu menunjukkan bahwa di tanah Haramain sendiri terdapat hal menarik, terutama corak dan arah perkembangan pemikiran para santri dan ulama Nusantara di sana. Ternyata, sekalipun para santri Nusantara belajar ilmu agama di Mekah dan sekitarnya, namun pada umumnya guru-guru yang mengajar mereka adalah juga ulama yang berasal dari Nusantara. Faktor ini menjadikan ulama ?keluaran? Haramain pada masa itu tetap konsisten dengan mazhab Syafi?i dan teologi Asy?ariyah, dan tidak menjadi pengikut Wahabiyah, sebagai faham keagamaan yang dominan di Saudi Arabia waktu itu.
Selain tidak terpengaruh secara signifikan oleh faham Wahabiyah, santri-santri Jawi abad ke-19 di Haramain lebih menggandrungi corak pemikiran fiqh. Bahkan lebih dari itu, corak tasawuf yang dikembangkan cenderung pada tasawuf amali, yaitu perpaduan antara tarekat Sammāniyyah dan al-Khalwātiyyah. Pada komunitas inilah Mu?ammad ?āli?, penerjemah Fat? al-Mubīn, bergabung menjadi santri Syekh Muhammad as-Sammānī, pendiri tarekat ini. Alasan ini pula yang mendorong penerjemahan Kitāb Fat? al-Mubīn ke dalam bahasan Melayu, sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan para santri Jawi dan umat Islam Nusantara terhadap literatur fiqh. Faktor inilah kemudian yang ikut mengubah corak faham keagamaan di Nusantara dari tarekat fatalistik ke faham keagamaan bercorak fiqh dan tasawuf amali.
Pokok-pokok Isi Naskah Pada awalnya, kitab Terjemah Fat al-Mubīn fī Syar al-Arbaīn karya Syekh Ibnu ?ajar al-?aitamī ini merupakan kumpulan hadis yang disertai syarah singkat berjudul al-Arba?īn Hadī? an-Nawawiyah fī al-A?ādī? an-Nabawiyyah ma?a Syar?ihā karya Imam Nawawi. Dengan demikian, secara substansial tidak ada perbedaan isi kitab ini dengan kitab Arba?īn Imam Nawawi. Kitāb al-Arba?īn, sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi dalam kata pengantar kitab tersebut, adalah kumpulan hadis yang membahas prinsip-prinsip Islam yang tidak terhingga nilainya, mencakup persoalan adab dan hukum-hukum. Masing-masing hadis merupakan prinsip penting, yang menjadi fondasi ajaran Islam. Sebagai karya lanjutan yang pada awalnya adalah sebuah kitab hadis, Terjemah Fat? al-Mubīn termasuk kategori literatur Islam multiwajah.
Dari perspektif penulisan sebuah karya keagamaan, di dalam kitab ini ditemukan berbagai hal yang berhubungan dengan prinsip keagamaan. Pertama, dari dasar penulisannya, kitab Fat? al-Mubīn memulai pembahasannya dari hadis-hadis terpilih yang kemudian diberi syarah. Paling tidak, dalam kitab ini terdapat 42 hadis pilihan yang ditempatkan sebagai dasar pokok pembahasan, kemudian ditambah dengan beberapa hadis lain yang digunakan untuk memperkuat syarah yang dikemukakan. Kedua, dilihat dari keragaman hadis yang dikutip, kitab ini merepresentasikan sebuah aspek kajian yang cukup luas. Dari sisi ini, kitab ini dapat dikategorikan sebagai literatur umum, yang dalam sistem kategorisasi perpustakaan termasuk kelompok kode 297.00. Ketiga, dilihat dari kuantitas pembahasan dalam syarah yang dikemukakan, pembicaraan tentang fiqh termasuk pokok bahasan yang paling besar jumlahnya dibanding dengan pembicaraan mengenai aspek lainnya. Karena luas dan dalamnya pembahasan fiqh, seolah-olah kitab ini adalah sebuah kitab fiqh. Hal ini semakin diperkuat lagi dengan beberapa pembahasan tentang fiqh, sebagai catatan tambahan yang dimuat pada bagian-bagian akhir kitab ini. Dengan demikian, kitab Fat? al-Mubīn dapat disebut sebagai literatur keislaman yang memuat banyak hal tentang ajaran agama, dengan konsentrasi khusus pada fiqh Islam. Hadis-hadis yang dikutip dalam kitab ini sangat beragam. Sepertinya, hadis-hadis tersebut dirujuk dan dikumpulkan dari berbagai kitab hadis. Terdapat 42 hadis yang dikutip sebagai dasar pembahasan dalam kitab ini, di antaranya: amal harus dengan niat, iman, islam dan ihsan. Dari syarah yang dikemukakan, tampak jelas bahwa kecenderungan penulis buku ini lebih kuat pada persoalan fiqh. Sebab, isi kitab setebal 28 kuras tersebut, hampir 20 kuras membicarakan tentang fiqh, sedangkan selebihnya membahas tentang akidah dan akhlak. Sebagai contoh, uraian hadis pertama hingga ketiga, boleh dikatakan sangat lengkap untuk sebuah pengkajian tetang rukun Islam. Hal-hal yang dibahas di sini mulai dari persoalan niat, taharah, salat fardu dan sunat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan pada bagian akhir kitab ini sengaja dibuat penambahan di luar syarah dari 42 hadis yang dikutip. Uraiannya meliputi pembahasan tentang hukum binatang buruan, sembelihan, kurban, akikah, khitan, dan hukum makanan. Hal ini merupakan petunjuk bahwa penulis kitab ini adalah seorang ahli dalam bidang ilmu fiqh. Seperti kitab sumbernya, pembahasan dalam kitab Terjemah Fat? al-Mubīn tidak diurut secara sistematis. Hal ini dapat dimaklumi, karena agaknya penulis sangat terikat dengan susunan hadis yang seolah-olah sudah given dari penyusun pertamanya, Imam Nawawi.
Gambaran isi kitab yang tidak sistematis dapat dilihat dari: 1) pembahasan tentang iman dan tauhid yang ditempatkan di dua tempat terpisah, yang diselingi dengan persoalan fiqh yang diuraikan sangat panjang; 2) pembahasan tentang fiqh tersebar di berbagai tempat, dan dua pokok bahasan penting ditempatkan di dua bagian yang terpisah; dan 3) pembahasan tentang akhlak juga ditempatkan secara tidak teratur, karena sering diselingi dengan kajian tentang hukum fiqh. Dilihat dari topik-topik bahasannya, kitab Terjemah Fat? al-Mubīn mengungkap banyak hal. Secara garis besar, topik-topik bahasan dimaksud dapat dikemukakan di sini: 1. Pembahasan tentang iman atau tauhid. Seperti sudah dikemukakan, pembahasan tentang iman ditulis dalam dua tempat terpisah. Pada bagian pertama pembahasan ini merupakan penjabaran dari Syahadatain sebagai urutan pertama rukun Islam yang disebut dalam hadis kedua.
Uraian tentang tauhid memuat pembahasan yang mendalam tentang sifat-sifat Allah dan para rasul. Pembahasan ini dihimpun dalam satu rangkaian yang disebutnya sebagai al-?Aqā?id al-Khamsūn (lima puluh akidah). Pokok-pokok pembahasan ini jelas merujuk pada faham Ahlus Sunnah wal Jama?ah, perpaduan antara pemikiran kalam Asy?ariyah dengan Maturidiyah. Lima puluh akidah yang dipaparkan itu terdiri atas 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat Allah yang mustahil, satu sifat Allah yang jaiz, empat sifat rasul yang wajib, empat sifat rasul yang mustahil, dan satu sifat rasul yang jaiz. Pada bagian kedua pembahasan tentang iman difokuskan pada lima rukun iman lainnya, yaitu iman kepada malaikat, rasul dan nabi, kitab Allah, hari akhirat, dan takdir. Tampaknya uraian tentang kelima hal ini cukup mendasar dan sangat layak dibaca oleh para pelajar pemula. Lebih dari itu, seperti halnya corak pemikiran Asy?ariyah, materi-materi yang dikedepankan di sini lebih banyak mereproduksi kembali pemikiran ulama ortodoks. Hampir tidak ditemukan uraian yang mempertemukan antara pemikiran rasional dan atau teoretis dengan teks-teks Qur?an dan Sunnah. Ungkapan-ungkapan mengenai akhirat, misalnya, pada kitab ini telah cukup berhasil mendramatisasi gambaran alam akhirat yang sangat menyeramkan, dengan suasana huru-haranya yang mengerikan. Pada sisi lain, dalam kitab ini pembahasan tentang ihsan dipadukan dengan pembahasan tentang iman. Menurut penulis kitab ini, ihsan termasuk kajian dari iman, karena berhubungan dengan keikhlasan. Ikhlas sebagai wujud ihsan, menurut kitab ini, sangat erat kaitannya dengan iman. 2. Pembahasan tentang fiqh. Pembahasan mengenai fiqh ditulis secara panjang lebar dalam kitab ini. Syarah terhadap hadis yang berkenaan dengan salat, puasa, zakat, dan haji mendominasi isi kitab ini, sehingga tampak tidak seimbang dengan syarah terhadap hadis lainnya. Pembahasannya yang cukup luas dan dalam memberi kesan seolah-olah kitab Terjemah Fat? al-Mubīn adalah sebuah kitab fiqh. Sebagai kitab yang ditulis oleh seorang pengikut faham Ahlus Sunnah wal Jama?ah, pendapat-pendapat hukum yang diturunkan merujuk pada mazhab Syafi?i. Hal ini terlihat dari aturan-aturan dan tata cara ibadah yang dipaparkan, seperti taharah dan salat. Hampir seluruhnya mengikuti pemikiran hukum Syafi?iyah. Lebih spesifik lagi, isi kitab ini cenderung monolitik, tidak memberi ruang perbandingan atau pengungkapan perbedaan pendapat. Hal ini memberi kesan, kitab Terjemah Fat? al-Mubīn dipersiapkan untuk pembaca Syafi?iyah murni. Hal yang mungkin menarik perhatian, dilihat dari fungsi kitab Fat? al-Mubīn sebagai kitab syarah hadis, adalah munculnya pembahasan tentang binatang buruan, sembelihan, kurban, akikah, khitan, dan hukum makanan dan minuman. Topik-topik ini tidak jelas apakah merupakan hasil karya Ibnu ?ajar al-?aitamī (penulis kitab Fat? al-Mubīn) atau merupakan gagasan dari penerjemahnya (Mu?ammad ?āli?). Hal yang pasti adalah topik-topik tersebut sama sekali tidak terkait dengan salah satu dari 42 hadis yang disyarah. Tentu kesan yang muncul tidak lain bahwa Terjemah Fat? al-Mubīn memang lebih mengutamakan persoalan fiqh daripada bidang keislaman lainnya. 3. Pembahasan tentang bid?ah. Dalam kitab ini terdapat sedikit pembahasan tentang bid?ah, sebagai penjabaran hadis ke-5. Pendapat tentang bid?ah dibahas penulis dalam rangka mengkritisi pendapat dan praktik-praktik keagamaan para penganut faham tarekat. Menurut kitab ini, terdapat beberapa faham dan praktik keagamaan di kalangan penganut tarekat yang menyimpang dari ketentuan Islam. Beberapa hal yang dipandang bid?ah antara lain adalah faham tarekat yang mengharamkan yang halal, puasa mutawaliyat (terus-menerus), puasa pada hari tasyriq, salat sunat tiga rakaat pada nisfu Sya?ban dengan sejumlah bacaan, dan beberapa praktik ibadah lainnya. 4. Pembahasan tentang akhlak. Pembahasan tentang akhlak merupakan syarah dari beberapa hadis yang dijadikan dasar uraian. Uraian mengenai akhlak banyak dikaitkan dengan aspek keimanan dan hukum. Dalam hal ini, akhlak dipandang sebagai dasar kesempurnaan iman, dan selanjutnya norma-norma akhlak diformalkan seperti halnya hukum fiqh. Pola pemikiran semacam ini jelas mengindikasikan kuatnya pengaruh fiqh dalam penulisan kitab ini. Hubungan Naskah dengan Budaya Saat ini Pada dasarnya penerjemahan Kitāb Fat? al-Mubīn bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam etnis Melayu Nusantara yang sedang berusaha memperluas wawasan keislaman. Kitab ini merupakan prototipe dari seperangkat pemikiran yang berorientasi pada penegasan dan penjelasan prinsip-prinsip keislaman yang sangat relevan dengan kondisi pengetahuan umat Islam yang masih minim. Dilihat dari konsep-konsep dan ajaran yang disampaikan, penulis kitab ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan dasar yang perlu dimiliki oleh umat Islam saat itu. Saat ini tentu sudah sangat banyak ditemukan literatur dengan pembahasan yang sama di Indonesia, baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia. Itulah sebabnya, Azyumardi Azra menyebut kitab dasarnya, al-?adī? al-Arba?īn karya Imam Nawawi, sebagai tulisan yang diperuntukkan bagi pembaca umum, bukan untuk ahli yang mendalami ilmu agama. Namun demikian, kitab ini memperlihatkan suatu hal penting yang masih memiliki relevansi dengan perkembangan budaya umat Islam saat ini. Paling tidak, pola penyajian kitab terjemah Fat? al-Mubīn yang sangat menekankan keyakinan tentang akhirat dan ajaran-ajaran akhlak dipandang sebagai counter terhadap kecenderungan hidup materialistik-hedonistik dan destruktif yang dilihatkan banyak orang saat ini. Penilaian sejumlah ilmuwan dan aktivis Muslim fundamentalis bahwa kerusakan moral dan kedangkalan akidah sebagian umat Islam saat ini berkaitan dengan corak pemahaman agama yang bersifat rasional, pada satu sisi, agaknya dapat diterima. Untuk itu, pola penjelasan tentang peristiwa-peristiwa akhirat secara dramatis dan penegasan masalah akhlak yang dikaitkan dengan persoalan hukum dapat dipandang sebagai alternatif pemahaman keagamaan yang perlu dihidupkan kembali saat ini. Kesimpulan Dari paparan yang sudah disampaikan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Naskah-naskah Islam klasik banyak ditemukan di Sumatera Utara, baik yang sudah ada dalam katalog perpustakaan dan museum, maupun yang belum. Bahkan menurut perkiraan, masih banyak naskah Islam klasik yang belum ditemukan, yang disimpan oleh perorangan atau lembaga pendidikan. 2. Topik-topik bahasan kitab Terjemah Fat? al-Mubīn mencakup pembahasan tentang iman atau tauhid, fiqh, bid?ah, dan akhlak. 3. Kitab Terjemah Fat? al-Mubīn tidak dapat dikategorikan sebagai terjemahan murni dari kitab tersebut, karena penerjemah sendiri menambahkan beberapa topik bahasan di luar konteks pada halaman-halaman bagian akhir. Rekomendasi Mengingat pentingnya pengumpulan, pemeliharaan dan penggalian manuskrip-manuskrip Islam klasik, paling tidak ada dua rekomendasi yang perlu dilaksanakan dalam waktu dekat: 1. Perlu pengkajian lebih banyak dan mendalam terhadap naskah-naskah peninggalan ulama masa lalu. Hal ini amat diperlukan, karena ternyata banyak pengetahuan Islam yang tersimpan dalam manuskrip klasik yang belum tergali dan terpublikasikan dengan baik. Paling tidak amat diperlukan usaha-usaha penyuntingan (ta?qīq) terhadap naskah-naskah Islam klasik agar lebih banyak diketahui oleh para penggali dan pengembang (mubalig) ilmu pengetahuan keislaman. 2. Perlu dibentuk lembaga pengkajian naskah-naskah klasik secara nasional dan mempunyai cabang-cabang di pusat-pusat islamisasi periode awal, seperti di Aceh dan Sumatera Utara. Melalui lembaga khusus ini diharapkan muncul kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, dan penggalian khazanah Islam klasik secara lebih intensif.
(Dikutip dari www.depag.web.id * Daftar Pustaka Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Penerbit Mizan, 1994. Farhūd, Mu?ammad as-Su?ūd. al-Hadiyyah as-Sa?diyyah Syar? al-Arba?īn an-Nawawiyyah, Juz I. Hijaj: Mahabah Hijājī A?mad ?Abd al-La?īf Zahrān, 1972. Gibb, H.A.R. and J.H. Kramees (Eds.), Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden: E.J. Brill, 1961.)



